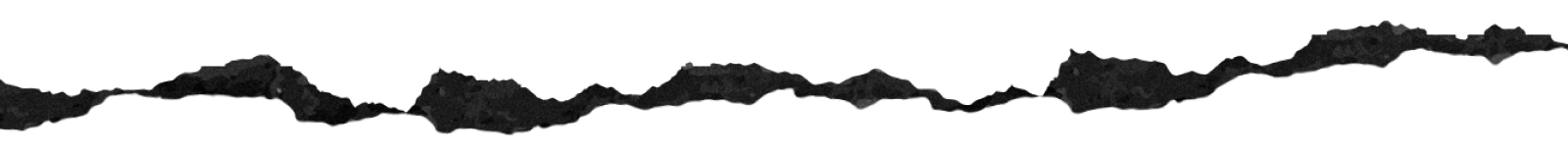Covid-19, Penyakit Baru, dan Krisis Iklim
16/04/2020
Ditulis oleh: Widia Primastika (Trend Asia)
Kerepotan kita akibat bencana banjir dan tanah longsor yang sempat menghampiri masyarakat Indonesia pada pembuka tahun 2020 kini telah bertambah dan bertubi-tubi: wabah Covid-19. Coronavirus Disease atau COVID-19 merupakan penyakit baru yang ditemukan pada tahun 2019 di Wuhan, Cina, dan belum pernah diidentifikasi pada manusia [1]. Penyakit ini terjadi karena penderita terinfeksi oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-Cov-2).
Dua bulan lebih setelah virus ini ditemukan, WHO pun menetapkan Covid-19 sebagai pandemi karena begitu cepat menyebar ke negara lain dalam satu waktu. Jumlah pasien di negara lain pun terus bertambah, meski pertumbuhan di negara asalnya, Cina, tak secepat dulu.
Gambar 1. Kasus COVID-19 di dunia per tanggal 30 Maret 2020.
Sumber: European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Per tanggal 30 Maret 2020 pukul 10.00 CET, WHO mencatat 693.224 kasus terkonfirmasi dengan 33.106 kematian. Dari jumlah tersebut, negara yang memiliki kasus Covid-19 terbanyak yakni Italia, dengan jumlah kasus mencapai 97.689 dengan 10.781 kematian, diikuti dengan Cina (negara ditemukannya kasus pertama) dengan jumlah kasus mencapai 82.447 dengan jumlah kematian mencapai 3.310. Sedangkan di Indonesia, berdasarkan situs kawalcovid19.id, per tanggal 31 Maret 2020 pukul 19.10 terdapat 1.414 kasus terkonfirmasi dengan jumlah kematian 122 pasien. Indonesia merupakan negara dengan angka kematian tertinggi di Asia Tenggara dan dengan persentase kematian akibat Covid-19 tertinggi di dunia.
Gambar 2. Peta distribusi jumlah penderita (kumulatif) kasus COVID-19 per 100.000 orang per tanggal 30 Maret 2020.
Sumber: European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Hingga kini, hewan yang menjadi sumber pandemi masih menjadi misteri. Para ilmuwan pun masih adu cepat menemukan asal-usul penularan penyakit ini. Berdasarkan analisis sementara dari para ilmuwan, ketika 41 kasus pneumonia parah pertama kali diumumkan di Wuhan pada Desember 2019 lalu, banyak pasien terhubung dengan pasar basah yang kerap menjual daging satwa liar. Hewan-hewan tersebut ditumpuk di dalam kandang -kelinci ditumpuk dengan musang-[2] [3] [4]
Bagaimana hewan bisa membawa virus bagi manusia?
Profesor Tim Benton, direktur riset Tim Emerging Risks di Chatham House, sebuah lembaga analis kebijakan independen, melalui artikelnya di BBC, memaparkan tentang pesatnya perkembangan penyakit menular dari hewan ke manusia selama 50 tahun terakhir. Ia memulai dari krisis HIV/Aids pada sekitar tahun 1980-an. Penyakit ini asalnya dari kera besar. Setelah HIV/AIDS, ada penyakit flu burung yang dibawa oleh unggas pada tahun 2004-2007, kemudian flu babi tahun 2009, diikuti dengan SARS dari kelelawar melalui musang, dan Ebola dari kelelawar.
Jim Robbins, dalam analisisnya di The New York Times pada 2012 lalu mengatakan bahwa epidemi yang dialami dalam beberapa dekade belakangan ini tidak terjadi begitu saja. Robbins menyebut, hal tersebut merupakan akibat dari perbuatan manusia terhadap alam.
“Ternyata, sebagian besar penyakit merupakan masalah lingkungan. Enam puluh persen penyakit menular yang muncul yang memengaruhi manusia adalah zoonosis — mereka berasal dari hewan. Dan lebih dari dua pertiga dari mereka berasal dari satwa liar,” ujar Robbins dalam tulisannya.
Dalam artikel berjudul “Ecology of zoonoses: natural and unnatural histories” yang ditulis oleh Karesh, W.B., et.al. (2012) di The Lancet, mereka menyebut bahwa endemik seperti zoonosis (penyakit yang ditularkan dari hewan ke manusia) dan enzootik (tetap beradanya penyakit atau penyebab penyakit dalam sebuah lingkungan atau populasi binatang tertentu) menyebabkan sekitar satu miliar kasus penyakit pada manusia dan jutaan kematian setiap tahun.
Karesh, dkk. mengaitkan zoonosis yang terjadi tersebut dengan alih fungsi lahan dalam skala besar yang memengaruhi keanekaragaman hayati dan hubungan antara hewan inang, manusia, dan patogen. Ada beberapa kasus yang mereka sebut dalam esainya, seperti penyakit malaria dan Lyme [6]. Kedua penyakit tersebut merupakan akibat dari deforestasi yang meningkatkan interaksi antara patogen, vektor (organisme perantara), dan inang.
Pada kasus malaria misalnya, Patz, J.A., et.al. melalui laporannya yang berjudul “Unhealthy Landscapes: Policy Recommendation on Land Use Change and Infectious Disease Emergence” menerangkan peningkatan kasus malaria dan/atau vektornya di Afrika bebarengan dengan meningkatnya penggunaan lahan dan pola pemukiman manusia.
“Ketika hutan tropis ditebangi untuk aktivitas manusia, mereka biasanya dikonversi menjadi lahan pertanian atau penggembalaan. Proses ini umumnya diperburuk dengan pembangunan jalan, mengakibatkan erosi dan menjadikan tempat yang mulanya tak bisa diakses menjadi terjajah oleh manusia,” ujar Patz, dkk.
Kemudian, tanah yang terbuka dan gorong-gorong yang mengumpulkan air hujan di beberapa daerah tersebut rupanya menjadi tempat hidup yang lebih cocok untuk larva nyamuk anopheline, si penular malaria, ketimbang hidup di hutan utuh.
Contoh lain yakni virus Nipah yang terjadi di Asia Selatan dan virus Hendra di Australia, keduanya merupakan genus virus henipah. Virus ini berasal dari kelelawar buah atau Pteropus vampyrus. Virus henipah pada kelelawar telah mengalami evolusi selama jutaan tahun. Suatu ketika, pada tahun 1999, di pedesaan Malaysia, seekor kelelawar diduga telah menjatuhkan sepotong buah yang dikunyah ke dalam kandang babi hutan. Akibatnya, babi itu menjadi terinfeksi virus dan menyebar ke manusia. Virus Nipah mengakibatkan 276 orang Malaysia terinfeksi, dengan jumlah kematian mencapai 106 jiwa, penderita lainnya banyak yang mengalami kelainan neurologis permanen dan melumpuhkan.
“Penyakit menular yang muncul merupakan jenis patogen baru atau patogen lama yang telah bermutasi menjadi baru, seperti flu yang terjadi setiap tahun,” ungkap Robbins dalam artikelnya di The New York Times.
Benarkah penyakit baru berkaitan dengan krisis iklim?
Keterkaitan antara krisis iklim dan kehadiran penyakit baru masih menjadi perdebatan di kalangan ilmuwan. Robinson Meyer dalam laporan berjudul “The Zombie Diseases of Climate Change” yang ia tulis untuk The Atlantic menulis tentang permafrost atau tanah atau batu yang membeku atau tertutup lapisan es selama bertahun-tahun. Lapisan aktif ini merupakan tempat yang baik bagi mikroba dan bentuk kehidupan lainnya hidup bahkan hingga satu juta tahun.
Namun, karena musim panas yang panjang dan musim dingin menghangat, lapisan es tersebut pecah dan sebagian mencair. Belakangan ini, permafrost yang baru aktif ini dipenuhi dengan bangkai purba yang terkubur: tanaman, hewan, dan lumut. Mencairnya lapisan es ini tentu sangat mungkin mengaktifkan kembali mikroba penyebab penyakit seperti bakteri dan virus yang tak bisa bergerak karena membeku.
Jasmin Fox-Skelly dalam reportasenya untuk BBC memaparkan tentang kejadian pada Agustus 2016 di Semenanjung Yamal di Lingkaran Arktik. Saat itu, seorang anak laki-laki berusia 12 tahun meninggal dan setidaknya dua puluh orang dirawat di rumah sakit setelah terinfeksi oleh antraks.
Lebih dari 75 tahun yang lalu, seekor rusa kutub yang terinfeksi antraks meninggal dan bangkainya tertutup oleh lapisan es atau permafrost hingga pada musim panas 2016, lapisan es mencair karena gelombang panas. Antraks yang ada dalam jenazah rusa kutub itu turut ke air dan tanah di dekatnya, lalu masuk ke bahan pangan. Akibatnya, lebih dari 2000 rusa dan sejumlah manusia terinfeksi.
“Permafrost adalah pelestari mikroba dan virus yang sangat baik, karena dingin, tidak ada oksigen, dan gelap,” ujar ahli biologi evolusioner Jean-Michel Claverie dari Universitas Aix-Marseille di Prancis. “Virus patogen yang dapat menginfeksi manusia atau hewan mungkin terawetkan di lapisan es yang lama, termasuk beberapa yang telah menyebabkan epidemi global di masa lalu,” tambahnya.
Pada penelitian tahun 2005, ilmuwan NASA pernah berhasil menghidupkan kembali bakteri di kolam beku Alaska yang berusia 32.000 tahun bernama Carnobacterium pleistocenium dan dua tahun setelahnya mereka berhasil menghidupkan bakteri berusia 8 juta tahun yang sempat tidak aktif di es yang berada di bawah permukaan gletser di lembah Beacon dan Mullins di Antartika, serta sebuah bakteri berusia lebih dari 100.000 tahun.
Memang tak semua bakteri bisa hidup kembali setelah dibekukan di lapisan es. Namun dalam kasus Antraks, ia bisa aktif lagi karena membentuk spora yang sangat keras dan mampu menahan beku lebih dari satu abad.
Hubungan lain antara penyakit menular dan kerusakan lingkungan yang dipaparkan WHO yakni tentang kondisi tubuh manusia yang semakin rentan. Hal ini sebabkan oleh kualitas air minum dan lahan tempat menanam yang telah terkontaminasi, serta penurunan kualitas udara.
Akibatnya, ketika penyakit baru muncul, akan ada kelompok rentan yang berisiko terserang penyakit karena minimnya fasilitas kebersihan dan kesehatan. Ini diperparah dengan rendahnya nutrisi yang masuk ke tubuh mereka sehingga memengaruhi sistem kekebalan tubuh.
Tim Benton, Direktur Riset dalam Tim Emerging Risks di Chatham House melalui esainya di BBC menjelaskan bahwa penyakit infeksi juga lebih rentan terjadi di perkotaan karena mereka berada dalam kawasan yang lebih padat, sehingga sangat mungkin menghirup udara dan menyentuh berbagai benda yang sama.
Dalam kasus Covid-19, para peneliti memang belum menemukan penyebab kemunculan virus ini secara pasti, tapi Benton mengajak kita untuk tak mengabaikan kerusakan lingkungan ketika terjadi pandemik.
“Dengan mengakui bahwa penyakit baru muncul dan menyebar sebagai bagian dari perubahan lingkungan, akan membuat posisi kita lebih kuat untuk memerangi pandemi yang terhindarkan untuk terjadi lagi di masa depan,” ujarnya.
Daftar Pustaka:
[1] WHO. Coronaviruses. (https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses).
[2] “Mystery deepens over animal source of coronavirus” dipublikasikan di Nature (https://www.nature.com/articles/d41586-020-00548-w).
[3]“How China’s ‘Bat Woman’ Hunted Down Viruses from SARS to the New Coronavirus” dipublikasikan di Scientific American (https://www.scientificamerican.com/article/how-chinas-bat-woman-hunted-down-viruses-from-sars-to-the-new-coronavirus1/).
[4] “From Bats to Human Lungs, The Evolution of A Coronavirus” dipublikasikan di The New Yorker (https://www.newyorker.com/science/elements/from-bats-to-human-lungs-the-evolution-of-a-coronavirus)
[5] “Coronavirus: Why are we catching more disease from animals?”, dipublikasikan di BBC (https://www.bbc.com/news/health-51237225).
[6] “The Ecology of Disease” dipublikasikan di The New York Times (https://www.nytimes.com/2012/07/15/sunday-review/the-ecology-of-disease.html?login=email&auth=login-email&login=email&auth=login-email)
[7] Karesh, W.B. 2012. Ecology of zoonoses: natural and unnatural histories. Dipublikasikan di The Lancet (https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(12)61678-X.pdf).
[8] Patz, J.A. 2004. Unhealthy Landscapes: Policy Recommendations on Land Use Change and Infectious Disease Emergence. Environmental Health Perspective.
[9] “The Zombie Diseases of Climate Change”, dipublikasikan di The Atlantic (https://www.theatlantic.com/science/archive/2017/11/the-zombie-diseases-of-climate-change/544274/).
[10] “There are diseases hidden in ice, and they are waking up”, dipublikasikan di BBC Earth (http://www.bbc.com/earth/story/20170504-there-are-diseases-hidden-in-ice-and-they-are-waking-up).
[11] WHO. Climate change and human health – risks and responses. (https://www.who.int/globalchange/summary/en/index5.html)